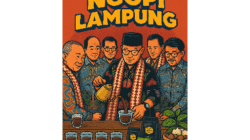Pimpinan dan anggota dewan itu sejatinya jongos rakyat. Tapi entah sejak kapan, jongos-jongos ini malah merasa jadi juragan.
Coba tengok kantor Dewan Kuta Bandar Lempuyang. Pelataran parkir penuh mobil mewah, bukankah gajinya dewan itu standar saja? Tapi kok bisa bergaya hidup bak pengusaha tambang?
Kalau ada rakyat datang? Staf akan bilang: “Bapak lagi rapat.” Padahal rapat itu cuma stempel kebijakan pemerintah. Sementara keputusan sudah lebih dulu diatur di ruang-ruang gelap.
Anggaran yang diajukan eksekutif pun sering hanya copy paste tahun sebelumnya. Anggota dewan? Tinggal angguk-angguk kepala.
Contoh baru, alokasi hibah pembangunan gedung senilai Rp 60 miliar. Meskipun mungkin secara regulasi tidak ada yang dilanggar, tapi apakah itu lebih urgen dari insentif ketua RT yang lebih suka pending bayar alias kasbon dulu, bayar rapel dua atau tiga bulan sekali.
Tapi beginilah situasi terkini di kantor Dewan Bandar Lempuyang: bukannya melayani, malah dilayani. Rakyat dianggap tamu tak diundang, padahal merekalah pemilik sah kursi-kursi itu.
Tak ada senyum tulus, tak ada sambutan hangat. Yang ada justru kesan: “Kalau tidak bawa amplop, jangan harap urusan lancar.”
Sungguh lucu. Para anggota dewan mungkin lupa kalau mereka bukan bos. Mereka lupa kalau gaji, tunjangan, bahkan mobil dinas yang mereka pakai itu dibayar dari pajak rakyat. Mereka lupa kalau titel “pejabat” itu bukan kemewahan, tapi amanah.
Kalau sudah begini, jangan heran rakyat makin muak. Lama-lama, rakyat bisa sadar bahwa jongos yang lupa jadi jongos ini cuma kuat karena diamnya rakyat. Dan kalau rakyat sudah tidak mau diam lagi, entah bagaimana nasib para “juragan gadungan” itu.
Ingkar Takdir Sebagai Jongos
Birokrat, dalam hakikat awalnya, adalah pelayan. Mereka lahir dari sumpah dan janji sebagai abdi negara, yang dalam bahasa sederhana berarti abdi rakyat.
Namun, siapa yang bisa menyangkal bahwa hari ini para birokrat justru tampak ingkar pada takdirnya sebagai jongos masyarakat?
Lihatlah wajah-wajah pejabat di balik meja kayu besar yang mengkilap. Betapa gagahnya mereka duduk di kursi empuk ber-AC, sementara di luar, antrean rakyat yang membawa berkas menunggu dengan wajah letih.
Ironis sekali, di tengah jargon pelayanan prima, yang tampak justru pelayanan yang dipersulit. Seolah-olah, rakyat yang mestinya menjadi majikan justru dianggap pengemis kebijakan.
Kantor-kantor pemerintahan hari ini lebih menyerupai showroom mobil ketimbang rumah rakyat. Lahan parkir penuh dengan deretan kendaraan mewah.
Pertanyaan sederhana: dari mana datangnya harta benda sebesar itu jika bukan dari “keringat” jabatan? Tentu rakyat bukan orang bodoh.
Mereka paham bahwa birokrat seharusnya tidak bergelimang harta yang tak sebanding dengan gaji resmi. Tapi publik memilih diam, entah karena pasrah atau sudah terlalu sering dikecewakan.
Kinerja legislatif yang diidamkan sebagai penyeimbang eksekutif pun semakin tumpul. Bukannya mengkritisi, mayoritas anggota dewan justru menjadi tukang stempel. Tahun demi tahun, program pembangunan yang diajukan eksekutif diloloskan dengan sedikit perdebatan.
Ironisnya, banyak dari program itu hanyalah salinan dari tahun-tahun sebelumnya—copy paste anggaran yang rutin, tanpa sentuhan gagasan baru. Lalu untuk apa rakyat mengutus wakil, kalau kerja mereka hanya mengangguk-angguk kepala?
Birokrat ingkar takdir berarti birokrat yang lupa bahwa ia hanyalah pelayan. Mereka terjebak dalam ilusi kuasa, padahal kuasa itu titipan. Mereka lupa bahwa kursi yang mereka duduki sesungguhnya adalah kursi rakyat. Mereka alpa bahwa kemewahan yang mereka pamerkan berdiri di atas pajak, iuran, dan keringat rakyat kecil.
Kritik ini bukan sekadar amarah. Ini pengingat. Bahwa jabatan publik adalah pengabdian, bukan kemewahan. Bahwa dewan adalah corong rakyat, bukan sekadar alat legitimasi kebijakan. Bahwa birokrat harus kembali ke hakikatnya: jongos masyarakat. Sebab, jika birokrat terus ingkar pada takdirnya, jangan salahkan rakyat jika kelak kehilangan kesabaran. (***)