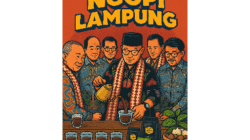Di tengah hiruk pikuk pembangunan, rapat-rapat formal, dan lembar-lembar laporan capaian kinerja, ada satu hal yang kerap luput dicatat: bagaimana lidah-lidah yang dahulu bersuara lantang tiba-tiba mengecil, melunak, lalu melengkung seperti sendok—siap menyuap dan menjilat.
Mereka yang dulu bersikap keras terhadap ketimpangan, kini menjadi barisan pengangguk yang memekarkan puja-puji seperti bunga plastik di ruang tunggu kekuasaan. Inilah realitas getir birokrasi kita: revolusi lidah menjadi penjilat.
Tak sedikit tokoh di birokrasi yang dulunya dielu-elukan karena “berjasa”—karena program-program populisnya, karena keberanian awalnya bersuara, atau sekadar karena latar belakang “pejuang” sebelum masuk ke struktur. Namun, ketika kursi dan kekuasaan mulai memberi kenyamanan, banyak dari mereka perlahan kehilangan idealisme. Lidah yang dulu berani menuntut kini sibuk memuji. Mereka yang dulu meneriakkan perubahan, kini menulis naskah sambutan penuh sanjungan.
“Sudah biasa, Mas,” kata seorang pegawai senior dalam bisik-bisik di pojok kantor, “yang keras sebelum dapat jabatan, biasanya lembek setelahnya.”
Memang, birokrasi punya cara membentuk manusia. Sistem yang terlalu hirarkis membesarkan rasa takut: takut kehilangan posisi, takut kehilangan akses, takut tidak dianggap penting. Maka, berjasa bukan lagi soal integritas atau keberanian, melainkan soal siapa yang lebih cepat menyesuaikan suara dengan selera penguasa. Siapa yang lebih trampil menjilat tanpa terlihat menjilat.
Di sekeliling orang kaya, orang penting, dan orang yang punya akses pada anggaran, lidah-lidah berubah menjadi kuas. Mereka melukis citra, membersihkan noda, menyanjung tanpa jeda. Bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan untuk tetap dianggap “berguna”.
Budaya patron-klien merajalela dengan wajah baru. Dulu, membungkuk karena takut. Sekarang, membungkuk karena ingin selamat atau ingin ikut menikmati remah kekuasaan. Di lingkungan ini, orang tak lagi berkata jujur. Kritik dianggap duri. Pertanyaan dianggap ancaman. Maka yang tumbuh adalah budaya kemunafikan yang nyaris sempurna—di luar tampak loyal, di dalam penuh intrik.
Lidah yang seharusnya jadi alat komunikasi berubah menjadi alat komodifikasi. Siapa yang paling trampil membungkus fakta dengan pujian, dialah yang paling mungkin naik ke panggung. Bahkan ada yang rela menyusun narasi-narasi palsu demi menjilat lebih manis, agar selalu dilirik oleh yang sedang di atas angin.
Karena sistem menyukai yang patuh. Karena kritik kerap dianggap pengkhianatan. Karena di banyak ruang birokrasi, kejujuran lebih cepat memiskinkan daripada menyejahterakan. Maka orang-orang waras memilih diam. Atau kalau bicara, cukup di warung kopi dan dalam grup WhatsApp pribadi. Di ruang publik, semua menjadi aktor yang memainkan peran sempurna.
Tak peduli seberapa rusaknya sistem, yang penting tampil manis di hadapan atasan. Lidah yang bisa bicara kebenaran kini lebih banyak digunakan untuk mencium tangan dan menjilat kebijakan.
Tulisan ini bukan untuk mereka yang nyaman menjilat, melainkan untuk mereka yang masih berani menjaga lidah tetap lurus. Birokrasi—sebagai ruang pelayanan publik—harusnya diisi oleh orang-orang dengan suara, bukan semata aktor yang andal bersandiwara.
Kita perlu kembali memuliakan kritik, membangun keberanian untuk menyampaikan yang tak ingin didengar, dan mengubah budaya “asal atasan senang” menjadi budaya pelayanan yang jujur dan transparan. Karena ketika lidah berhenti berkata jujur dan hanya menjadi alat penjilatan, maka kita bukan sedang membangun, tapi sedang memperluas ruang kemunafikan. Kita tak butuh lebih banyak penjilat. Kita butuh lebih banyak penjaga nurani.
Tulisan ini sekedar catatan pengingat tanda sayang. Kalau kata host PK (Perang Koin) ngetop- Anda BAPER Cabut.(*)