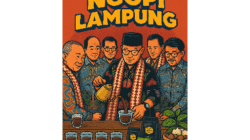Episode terbaru “drama Lampung” kembali tayang. Judulnya: OTT LSM. Dua aktivis diamankan aparat, dengan tuduhan memeras pejabat lewat ancaman di WhatsApp dan isu akan menggelar demo.
Di atas kertas, cerita ini sederhana: ada pejabat merasa diintimidasi, ada aktivis yang dituding memanfaatkan kritik untuk mencari “uang damai”.
Namun, seperti biasa, Lampung tidak pernah sesederhana kertas perkara. Versi aparat menyebut ada komunikasi, ada ancaman, hingga uang yang akhirnya berpindah tangan. Singkatnya: pemerasan.
Versi aktivis yang ditangkap justru berbalik arah: “Kami tidak pernah minta, tidak pernah menerima. Pertemuan di mall itu pun atas undangan utusan pejabat. Kalau kemudian uang itu tiba-tiba diselipkan lewat plastik hitam ke mobil, siapa yang sebenarnya bermain?”
Pertanyaan itu menggantung, dan publik kembali terbelah: Apakah ini benar murni penegakan hukum? Atau sekadar cara lama untuk menutup mulut suara-suara kritis?
Fakta lain ikut menambah bumbu: surat perintah penangkapan ternyata sudah keluar jauh sebelum OTT. Artinya, yang bersangkutan sudah lama jadi target operasi.
Lalu, mengapa tetap diatur pertemuan di mall, lengkap dengan “uang damai” yang akhirnya jadi barang bukti?
OTT semestinya menjadi cara efektif membongkar pemerasan. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjelma instrumen pembungkaman.
Modusnya mirip: lawan politik, aktivis, atau LSM dipancing untuk masuk ke jebakan. Begitu uang berpindah tangan—entah siapa yang lebih dulu menginisiasi—label pemeras pun menempel, reputasi hancur, suara kritis pun bungkam.
Kita memang perlu jujur. LSM juga tak semuanya steril; ada yang memang hidup dari “menjual tekanan”.
Tapi pejabat pun tidak semuanya bersih; ada yang menghalalkan segala cara agar kritik lenyap.
Di titik ini, publik berhak curiga: siapa yang benar-benar jadi korban, siapa yang sedang memainkan lakon, dan siapa yang paling diuntungkan?
Kasus ini sekali lagi menunjukkan, Lampung masih jadi panggung tarik-menarik antara kekuasaan, aktivisme, dan aparat. OTT kali ini bisa jadi babak awal, bisa pula jadi tirai penutup.
Publik hanya bisa menunggu: apakah aparat berani membuka semua fakta sampai tuntas, atau justru berhenti di permukaan, menyisakan aroma rekayasa yang menyengat.
Sebab, pada akhirnya, persoalan bukan semata pemerasan atau pembungkaman. Persoalan utamanya adalah: apakah hukum benar-benar bekerja untuk kebenaran, atau hanya sekadar alat untuk menyingkirkan yang tak diinginkan? (***)