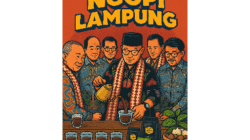Dalam perjalanan birokrasi yang seperti kereta panjang yang melaju kencang, selalu ada perasaan was-was tentang siapa yang tetap berada di dalam, siapa yang terseret, dan siapa yang tertinggal di stasiun — bahkan tanpa sempat berpamitan.
Di balik riuhnya pergerakan itu, ada bisik-bisik yang sayup-sayup terdengar di telinga: “Gerbong kedua sudah mulai berjalan.”
Itulah tanda-tanda perubahan, atau setidaknya sinyal bahwa formasi baru sedang dibentuk. Mereka yang peka tentu lekas merapikan diri, berlari, berpegangan erat pada gerbong yang masih bisa dicapai.
Sementara mereka yang lengah atau terlalu sibuk menatap diri di kaca jendela, sering kali baru tersadar ketika kereta sudah meninggalkan rel dan hanya menyisakan debu.
Saya, bukan bagian dari birokrasi ini, masih saja sering menerka-nerka — dengan kebodohan yang terus berulang — apa sebenarnya yang membuat saya tercecer. Kesalahan apa yang saya buat? Kelalaian mana yang terlewat? Saya coba susuri ulang langkah demi langkah, evaluasi demi evaluasi, namun jawaban itu sering tak kunjung datang.
Apakah karena saya kurang berjasa? Mungkin saja. Di ruang birokrasi, jasa dan kontribusi memang kerap diukur dengan parameter tak kasatmata.
Mungkin kiprah saya tak begitu tampak dibanding yang lain. Atau barangkali kontribusi itu ada, namun bukan pada waktu yang tepat, atau tidak dinilai cukup untuk menyelamatkan posisi di gerbong utama.
Atau, bisa jadi ada suara lain di antara para pengatur jalannya kereta ini yang berbisik: “Ah, nanti saja. Tidak penting-penting amat untuk dibawa.”
Satu kalimat sederhana, tapi cukup untuk menyingkirkan siapa pun dari prioritas. Lebih buruk lagi jika ternyata di antara mereka ada yang berpikir, “Toh kalau tercecer, dia juga tak akan merepotkan.”
Bagaimana rasanya menjadi yang tak merepotkan itu? Jujur saja, itu bukan pujian. Dalam dunia birokrasi, menjadi ‘tak merepotkan’ seringkali berarti dianggap tak cukup penting untuk dipertahankan.
Seperti perabot tua di pojok kantor yang dibiarkan berdebu karena tak ada yang butuh lagi, sampai waktunya dibuang atau diganti.
Karenanya, mungkin memang harus lebih vokal, lebih tegas menegaskan posisi. Tidak sekadar hadir, tapi juga terdengar. Tidak sekadar bekerja, tapi tampak dampaknya. Karena birokrasi — suka atau tidak suka — bekerja dengan ritme pengakuan. Siapa yang diam, akan dianggap usai. Siapa yang tak terdengar, perlahan dianggap hilang.
Saya mencatat ini sebagai pengingat diri. Bahwa dalam sistem yang terus berjalan seperti kereta yang tak pernah berhenti, setiap diri harus memilih: mau sekadar penumpang yang ikut, atau jadi penggerak yang mengokang laju.
Dan tentu saja, semua kembali kepada kita. Apakah ingin terus menerka dengan bodoh mengapa selalu tercecer, atau mulai menyusun ulang strategi agar suara dan langkah kita cukup kuat untuk tidak dilupakan.
Karena dalam birokrasi, diam adalah jalan cepat menuju stasiun terakhir. (*)